Teman Terbaik
“Mas, mangan sek!” ajak seorang bapak berusia 40 tahun kepada Dimas.
“Boleh, Pak. Indomie gorengnya satu pake telur mata sapi setengah matang
yo, Pak!” ucap Dimas pada pedagang Warmindo yang terletak di pinggir jalan
depan gerbang Fakultas Ilmu Pendidikan di mana Dimas menimba ilmu.
“Minumnya apa, Mas Dimas? tanya pedagang itu.
“Jus jeruk hangat, Pak.”
Meski letaknya di pinggir jalan, warung makan Indomie ini tidak pernah
sepi pembeli, bumbu khas yang digunakan Mas Purnomo sebagai bumbu tambahan
racikan sendiri menambah kenikmatan juga aroma Indomie sehingga menciptakan
menu lain daripada yang lain. Menu yang paling laris adalah menu Indomie
beceknya, siapapun yang melintas pasti akan segera melipir lalu memesan
semangkuk Indomie becek dan kembali lagi esoknya. Benar-benar enak sekali.
Rasanya tiada dua!
Siang itu matahari enggan sekali muncul, setia bersembunyi di balik
awan, ditambah rintik-rintik gerimis yang turun perlahan, menambah syahdu momen
makan Indomie kali ini. Terlihat banyak sekali mahasiswa yang
berbondong-bondong lari dari arah gerbang menuju warmindo milik Mas Pur. Mas
Pur tahu betul tempat strategis.
Seluruh kursi serta meja yang tadinya kosong kini dipenuhi mahasiswa
lapar juga sekaligus menepi dari rintik hujan, salah satunya Seto, begitu aku
memanggilnya, dia adalah mahasiswa Pendidikan Luar sekolah. Berbeda denganku
yang merupakan mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini.
“Ada Mas Dimas, toh? Mas Dimas sudah lama di sini? Tanya Seto padaku.
“Ah … belum, sudah pesan menu?” jawabku sekaligus menyodorkan selembar
menu padanya.
“Belum Mas. Aku dengar menu favorit di sini Indomie becek, ya? Ujar
Seto.
“Betul sekali. Monggo dipesan, To! Seruku.
Sebenarnya warmindo Mas Pur bukanlah tempat pertama pertemuan aku dan
Seto. Berhubung kami sama-sama mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, pastilah aku
pernah bertemu dengan Seto sebelum ini. Lelaki bertubuh jangkung dengan rambut belah
kanan klimis, berkulit putih dan berlesung pipi itu. Usia kami juga tidak
begitu jauh, bahkan bisa dibilang sebaya. Pembawaan Seto yang ramah dan humble
membuat siapapun yang mengenalnya pasti akan betah duduk dan bercerita
dengannya.
“Ngomong-ngomong dapet tugas Kewirausahaan juga gak semester ini? Tanya
Seto memulai pembicaraan saat aku sedang menikmati semangkuk Indomiegoreng
buatan Mas Pur yang bikin merem melek.
Dengan mulut dipenuhi Indomie, aku menjawab pertanyaan Seto seadanya,
“Hem … iya.”
Melihat hal itu, Seto menahan tawanya. Entah mengapa aku merasa klop
dengan Seto. Lelaki jangkung yang baru setengah jam duduk di sampingku.
Setelah selesai menikmati kelezatan Indomie goreng dan menyeruput jus
jeruk hangat, aku kembali menanyakan hal yang sama pada Seto. “Kalau kamu? Mau
buat usaha apa nih sama temen-temen untuk praktik kewirausahaan? Tanyaku.
Dengan sigap dan penuh percaya diri Seto menjawab pertanyaanku, “Aku dan
temen-temen berencana mau buka stand makanan aja, mau mengikuti jejak Mas Pur.
Jual Indomie keliling kampus.” Ucap Seto.
“Wah … Mas Pur punya saingan nih.”
Gelak tawa kami berdua memecah keriuhan warmindo milik Mas Pur, bersatu
dengan dentingan suara sendok beradu dengan piring masing-masing pelanggan.
***
Satu minggu setelah obrolan di
warmindo Mas Pur, aku dan Seto semakin akrab. Obrolan ringan namun padat selalu
menjadi bagian paling seru untukku. Jarak kos-kosan Seto yang tidak begitu
jauh menjadi alasan aku sering mengunjunginya. Sebenarnya bukan itu saja, aku
terlahir sebagai anak tunggal karena Mama dan Ayah bercerai saat aku berusia
lima tahun, juga Seto yang ditinggal mati ibunya saat berusia tiga tahun. Nasib
yang sama dan rasa hangat yang aku dapat tiap kali berdekatan dengan Seto
menambah intensitasku untuk mengunjunginya. Aku seperti memiliki saudara, hal
yang tak pernah aku dapatkan.
Namaku Dimas Baskara Putra, anak tunggal dari pernikahan kedua orang
tuaku. Pernikahan itu harus kandas di saat usiaku menginjak lima tahun, usia
anak-anak yang tidak begitu mengerti mengapa orang dewasa mudah sekali untuk
berjanji lalu kemudian mengingkari. Di usia lima tahun, aku juga harus rela
berjauhan dengan Mama karena Mama harus bekerja ke luar negeri demi menyambung
hidup. Perceraian karena keegoisan memang merugikan salah satu pihak. Ayah
tidak lagi memberi kami nafkah pasca bercerai, Mama terpaksa harus banting
tulang untuk menghidupi kami.
Hingga aku beranjak dewasa, kehidupanku seperti anak pada umumnya yang
dirawat dan dibesarkan oleh seorang nenek renta yang seharusnya aku lah yang lebih pantas merawat dan menemaninya. Hal itu menjadi tekad tersendiri
bagiku untuk dapat hidup mandiri jauh dari Mama. Tidak ada kedekatan antara aku
dan Mama selain ikatan darah.
“Aku nginap di sini ya, To,” ujarku pada lelaki jangkung yang tengah
asik memasak Indomie rasa kari ayam dengan cabe rawit banyak. Seto pecinta
pedas rupanya.
“Oke. Aman. Mau Indomie juga?” tawarnya padaku.
Langsung kusambut penawarannya dengan anggukan paling serius. Kebetulan
lapar juga sepulang kelas tadi. “Iya, aku mau juga, tambahin, ya. Pakai telur
ceplok dong!” pintaku tak tahu diri.
Belum lama aku mengenal Seto, ya … kira-kira baru satu bulan, tetapi
rasanya kami sudah saling kenal begitu lama. Seto juga anak tunggal, setelah
kepergian Ibunya karena kanker payudara, Seto tinggal berdua saja dengan
Bapaknya di rumah. Dulu, saat masih berusia tiga tahun, Seto sempat diasuh oleh
adik Bapaknya. Namun, karena harus melanjutkan sekolah ke kota dan akhirnya
menikah, Bibi yang merawat Seto terpaksa harus meninggalkannya juga. Pekerjaan
Bapak Seto? Bapak Seto bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit swasta
di kota, jarak rumah sakit dengan tempat tinggal mereka cukup jauh, Seto
bernasib sama. Jauh dari keluarga dan bertekad mandiri saat dewasa.
Sebuah panggilan terpampang di layar ponsel Seto, sekilas aku melihat
nama Bapak tertera di sana. Gegas aku panggil Seto untuk segera mengangkatnya.
“To! Bapak kamu nelpon, nih.”
Kudengar beberapa kali Seto menjawab “Iya Pak, besok Seto akan pulang.”
Entah ada perihal apa, Seto harus bergegas balik ke kampunya di
Mojokerto. Tak lama, ponselku juga berdering, terlihat sebutan sayang dariku
untuk wanita yang melahirkanku tertulis di layar pipih buatan China ini. “Halo, Ma. Iya, Alhamdulillah Dimas sehat dan
baik-baik saja. Ha? Kenapa buru-buru sekali, Ma? Malam ini? Yaudah deh iya.”
Dengan nada lemas aku menutup telepon dari Mama. Aku dan Seto
berpandangan satu sama lain. Dalam benakku, bisa-bisanya kami berdua kompak
diminta untuk segera pulang ke kampung, aku ke Sidoarjo, Seto ke Mojokerto.
Sebegitu kentalnya pertemanan kami, hingga semuanya harus kompak - batinku.
Subuh aku sudah sampai di depan rumah peninggalan nenek, rumah di mana
aku dibesarkan olehnya. Diantara dinginnya udara pagi menusuk tulangku, ada
senyum hangat dari pemilik rumah ini meyambutku di depan pintu. Semakin Mama
bertambah usia, aku melihat sorot teduh dari matanya juga wajah lembut penuh
ketabahan terpatri abadi di wajahnya.
“Alhamdulilah anak Mama sudah sampai, besok ada persiapan acara di rumah kita,” ucap Mama yang sudah tak sabar ingin membagikan kabar ini padaku, bahkan
ransel milikku juga belum sempat aku letakkan.
“Acara apa, Ma?” tanyaku penasaran.
“Mama mau nikah, Dim.”
Perkataan Mama seperti bom subuh bagiku, udara dingin menusuk
tulang kini berubah panas seketika. Aku gerah. Di usia yang tak lagi muda,
kenapa Mama bisa kepikiran untuk menikah lagi?
“Mama yakin? Apa karena Dimas tidak dekat dengan Mama sampai-sampai Mama
mau menikah lagi?” lirihku.
“Bukan, bukan karena itu. Mama tahu, kita tidak dekat dari dulu, tapi
bukan itu alasannya, Nak. Mama janda sudah lama sekali, sejak kamu kuliah di
Bandung, dan Mama kembali kerumah ini, tanpa ada siapapun, tanpa ada kamu,
sering kali Mama mendengar cerita miring tatkala ada teman sekolah Mama yang
datang mengunjungi Mama. Omongan miring itu lah yang menjadi tekad Mama, jika
ada seorang lelaki seusia Mama datang untuk menikahi Mama. Maka Mama akan
menerimanya.”
“Lelaki yang akan menikahi Mama bukan suami orang, ‘kan?” tanyaku
meracau, mulut dengan otak suka enggak sinkron deh. Kebanyakan nonton sinetron dengan ikon ikan lele duyung.
“Hush! Kamu ini. Mama bukan wanita seperti itu.”
Lewat obrolan mengejutkan itu, aku dan Mama kembali menghangat, sudah
lama sekali aku tidak berbincang dengannya, tidak dipeluk olehnya apalagi makan
masakannya. Aku yakin, pilihan Mama adalah yang terbaik untuknya.
Hari yang dinantikan Mama tiba. Rombongan keluarga mempelai pria yang
kutahu berasal dari Mojoekrto pun tiba. Diantara puluhan iring-iringan
mempelai, aku menangkap sosok yang tidak asing. Dari kejauhan saja aku sudah
bisa menebak siapa pria berkulit putih dengan rambut klimis itu. Dia lah Seto.
Apa dia mengantar pamannya? Makanya dia diminta kembali ke kampungnya?
“To, ngapain kamu?” tanyaku lirih mendekati tubuhnya.
“Kamu tinggal disini, Dim?” Seto justru berbalik bertanya penuh
keheranan.
“Mama kamu mau nikah, Dim?” lagi Seto bertanya seolah ingin memastikan.
“I-iya, To, kenapa? Jangan-jangan? Paman kamu yang mau menikahi Mamaku?”
tanyaku. Percakapan kami penuh tanda tanya.
“Bukan pamanku, Dim. Tapi Bapakku.” Seto menjawab pelan dengan kepala
menunduk.
Lagi-lagi Mama memberiku kejutan yang luar biasa, bagaimana bisa Bapak
Seto menikahi Mamaku, itu artinya kami akan menjadi saudara?
Kuraih pundak Seto, kudekatkan tubuhnya ke arahku, bibirku seketika
mengarah ke telinga Seto sambil berkata
“Doa kita dikabulkan Allah, To! Kita bakalan jadi saudara.”
Kutepuk-tepuk pundaknya, kepala Seto perlahan terangkat dengan wajah
memerah diikuti gelak tawa lebar dari kami berdua.
TAMAT





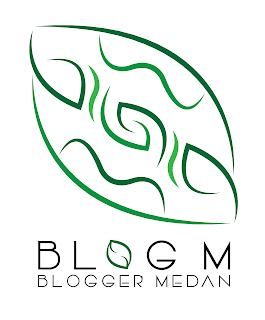
Hihi seru kali ya punya temen yang jadi sodara wkwkwkwk tapi ga mungkin juga sih, apalagi ortuku udah gaada. Tapi kasangy, temen-temen sendiri udah jej sodara karena sering laluiin hari bersama-sama
BalasHapus