Sujud Terakhir Ayah Part 10 (TAMAT)
Juli 11, 2022
0 komentar
Hai pembaca setia "Sujud Terakhir Ayah" tidak terasa cerita bersambung ini sudah memasuki part 10. Lewat cerita bersambung "Sujud Terakhir Ayah" saya sebagai penulis ingin menyampaikan banyak amanat atau pesan moral yang mungkin sering kita lihat di sekeliling kita.
Semoga seluruh pembaca dapat mengambil ibrah dari kisah fiktif ini. Nama tokoh, profesi tokoh serta latar belakang tokoh hanya fiktif belaka, ciptaan sang penulis. Jika ada kesamaan di dunia nyata. Saya sebagai penulis memohon maaf 🙏🏻
⭐⭐⭐
Setelah beberapa minggu berlalu, kondisi kesehatan Mahmud berangsur membaik. Bahkan kini ia sudah dapat melakukan aktivitasnya seperti sedia kala - berjualan peralatan shalat di pasar induk.
"Ayah sudah minum obat, kan?" tanya Mualimah yang baru datang dari rumah mereka.
"Iya sudah," jawab Mahmud.
"Sepulang sekolah, anak-anak akan temani Ayah, ya. Ibu pergi menghadiri pengajian di rumah Bu Tejo. Boleh, Yah?" ucap Mualimah.
"Iya boleh, Hafiz sudah berangkat ke pesantren, Bu?"
"Sudah, Ayah. Ayah masih marah dan kecewa pada anak kita? Ayah, berkah atau tidak hidupnya anak kita bergantung pada kita, kalau Ayah masih marah, ibu tidak akan memaksa Ayah untuk memaafkannya. Ibu hanya ingin keluarga kita baik-baik saja, anak-anak kita tumbuh besar, sehat dan berkah. Kalau kita sebagai orang tua masih menyimpan kekesalan, kasihan anak kita, Yah."
Bukan perkara mudah untuk melupakan apa yang telah terjadi, terlebih rasa sakit itu ditorehkan oleh darah daging sendiri.
Mahmud terdiam mendengar semua perkataan sang istri. Mualimah benar, kasih sayang orang tua sepanjang jalan, jalan yang akan dilalui seorang dengan penuh ridha orang tua akan membawa anak pada keberkahan. Dan Mahmud juga menginginkan itu untuk Hafiz. Dia sebagai Ayah tidak akan ingin kehidupan anak-anaknya kehilangan berkah hanya karena keegoisan dirinya yang terus menyimpan kekecewaan.
⭐⭐⭐
"Mualimah apa kabar? Sudah lama sekali tidak bertemu," sapa seorang wanita paruh baya, wajah mulus dengan kulit sawo matang, berpenampilan baik dan rapi dengan setelan gamis bewarna nude menghampiri Mualimah.
"Alhamdulillah Tati, saya sehat. Kamu apa kabar? Kok bisa ketemu di sini, ya?" tanya Mualimah bingung, wanita yang disapanya Tati adalah temannya saat SMA. Dan sekarang tinggal di Kota Padang ikut dengan suami yang bertugas di sana. Lalu, mengapa ada di sini?
"Iya, kebetulan saya lagi berkunjung ke rumah saudara, saudara saya mengajak saya kesini. Eh ketemu kamu." papar Tati. Ia memerhatikan tubuh sang teman SMA, sudah berbeda sekali dengan yang dikenalnya dulu. "Mualimah sekarang tambah cantik, ya. Sudah berapa anak kamu?" dengan antusias Mualimah pun menjawab, "Alhamdulillah, anak sudah tiga, dua ganteng dan satu cantik."
Obrolan demi obrolan pun terjadi, maklum saja, mereka sudah terpisahkan puluhan tahun sejak lulus SMA, wajar saja obrolan mereka tiada hentinya.
Acara pengajian pun selesai. Mualimah mengajak Tati untuk singgah ke rumahnya, berhubung Tati sudah lama sekali tidak bertemu dan berbincang dengan Mualimah, ajakan sang teman pun tak bisa diabaikan. Tati dan Mualimah sepakat untuk menghabiskan waktu senja mereka untuk mengobrol banyak hal. Kebetulan Tati juga tidak terburu-buru. Karena kepulangannya masih lusa depan.
"Wah... Asri sekali rumahmu, Mah. Sesuai dengan keinginanmu, ya?" ucap Tati takjub dengan penataan taman di pekarangan rumah Mahmud dan Mualimah.
"Jangan mengejek, Ti. Ini mah tidak sebesar rumah kamu di Padang. Saya sering lihat postingan kamu di facebook, meni rapi pisan..." jawab Mualimah.
"Asal rapi dan bersih, rumah besar atau kecil sama aja, yang penting penghuninya nyaman, tenang, rukun dan bahagia dia dalamnya," ucap Tati seraya memandangi beberapa koleksi Aglonema milik Mualimah. Koleksi bunga-bunga yang pernah hits pada musimnya, tersusun rapi di atas rak besi berwarna putih.
"Anak-anak kamu mana, Mah? Pada sekolah, ya? Tati kini mengalihkan pandangannya dan bertanya keberadaan anak-anak Mualimah yang tidak kelihatan sedari tadi.
"Yusuf dan Mumtaz langsung ke toko untuk membantu Ayahnya berjualan sepulang sekolah, kalau Hafiz, sedang ke pesantren. Kamu mau minum apa, Ti? Aku buatkan wedang jahe mau? Yuk sambil lihat-lihat foto anak-anakku."
Keduanya beranjak menuju ruang tamu, terpampang foto anak-anak Mualimah yang diabadikan dalam satu frame besar - foto keluarga. Dan ada satu frame lainnya khusus memperlihatkan wajah sang putra kebanggaan - Hafiz.
"Ini siapa, Mah? Wajahnya enggak asing banget?" tanya Tati yang tertuju pada sebuah foto seorang pemuda mengenakan jubah wisudanya.
"Ini Hafiz Ti. Anak sulungku, ini foto wisuda dia saat di Kairo. Dia lulusan pesantren dan mendapat beasiswa di Kairo."
Tati mulai bingung, pasalnya dua minggu yang lalu, ia berjumpa dengan Hafiz di salah satu kajian yang diisi olehnya. Hafiz sebagai penceramahnya. Kalau tidak salah, setelah menghadiri kajian, Tati beserta suami turut hadir di acara jamuan yang diadakan oleh Camat Kota Lima Puluh - Sumbar. Kebetulan suami Tati adalah panitia acara tersebut. Kalau tidak salah, Hafiz pernah menjawab bahwa kedua orangtua nya adalah pemilik pesantren, bukan seorang pedagang yang berjualan di pasar.
Sejuta pertanyaan mengusik Tati, hingga dengan hati gamang, ia mencoba menanyakannya pada Mualimah. Semoga Hafiz yang ia jumpai bukanlah anak sulung temannya. Jika memang benar, betapa hancur hati orang tua yang tidak dianggap keberadaannya oleh sang anak.
"Heum... Mualimah, aku mau bertanya sesuatu," ucap Tati malu-malu. Ia ragu, khawatir kalau pertanyaannya justru menyakitkan hati temannya.
"Tanya aja atuh... Kenapa sungkan gitu kamunya?"
"Dua minggu lalu, Hafiz anak kamu pergi mengisi ceramah di Sumatera?"
"Iya, kenapa? Kamu menghadiri kajiannya, ya?"
"Heum... Iya Mualimah. Anak kamu hebat, ya. Apa... Dia punya orang tua angkat di pesantren?"
"Enggak atuh. Dia masuk pesantren karena keinginan Ayahnya, dan juga berkat bantuan Pak RT sini, kebetulan Hafiz pada waktu itu sudah bisa menghapal juz 30, makanya bisa masuk pesantren,"
Hati Tati semakin gusar, ia takut pertanyaan dan ucapannya akan menjadi boomerang bagi keluarga ini.
Tak lama setelah Tati meneguk wedang jahe buatan Mualimah, masih di tengah rasa bersalahnya jika ia lanjutkan bertanya. Tiba-tiba suara deru mobil terdengar dari arah pekarangan. Terlihat seorang pemuda yang tidak asing baginya turun dari kendaraan roda empat buatan Jepang itu.
"Itu Hafiz, Ti. Yuk biar aku kenalin," ajak Mualimah penuh semangat. Ia pasti sangat bangga dengan pencapaian sang anak yang sekarang perlahan terkenal sebagai sang penceramah kondang.
Ragu-ragu Tati berjalan mengikuti langkah Mualimah menuju pintu menghampiri sang putra sulung temannya. Hatinya bercampur aduk, sedih dan kesal menjadi satu, bagaimana tidak sedih, Mualimah temannya, begitu bangga memperkenalkan sang anak, sedangkan anaknya sendiri? Malu mengakui identitas orang tuanya.
Tapi di sisi lain, Tati merasa kebohongan Hafiz harus diungkap, meski ia yakin, setelah kejadian sore ini, keluarga mereka tak akan lagi sama seperti dulu. Namun, agar Hafiz juga menyadari bahwa bagaimanapun dan siapapun orang tuanya, ia harus tetap bangga. Berkat mereka lah dia bisa seperti saat ini.
"Ini anakku, Ti. Ayo, Nak, salim bu Tati. Bu Tati ini teman Ibu, sekarang beliau tinggal di Sumbar ikut dengan suaminya yang tugas di sana. Raut wajah Hafiz berubah, masih jelas diingatannya siapa wanita di depannya yang sedang diperkenalkan Ibunya. Ia adalah jemaah kajian yang juga ikut menghadiri acara makan malam itu. Pasti ia juga dengar apa jawaban Hafiz saat ditanya apa pekerjaan orang tuanya.
"Saya sudah kenal, Mah. Tapi apa benar dia anakmu? Seinget ku, waktu itu dia bilang, kalau orang tuanya adalaj pemilik pesantren."
Wajah Hafiz pucat pasi, tak bisa ia mengelak, karena memanh itu yang diucapkannya. Ia hanya tidak menyangka dusta yang ia lakukan tempo hari cepat sekali terkuak, belum kering sakit hati dan kekecewaan sang Ayah. Kini ia harus menerima kekecewaan sang Ibu yang selama ini membelanya.
"Ii... Itu tidak benar. Ibu jangan berbohong, dosa, Bu. Tidak boleh mengada-ngada ketika berbicara jatuhnya fitnah," ujar Hafiz membela diri.
"Apa keuntungan saya berbohong? Justru saya ingin menyelamatkan hati teman saya agar tidak bertambah sakit hati mengetahui sikap anaknya seperti kamu," cecar Tati. Suaranya bergetar, ia sebagai seorang Ibu bisa membayangkan bagaimana sakitnya seorang Ibu yang tidak dianggap oleh anaknya sendiri.
Mualimah yang berdiri di samping Tati, kini tak kuasa menahan beban tubuhnya, ia ambruk, tertuduk sambil memegangi dadanya yang ngilu. Tati dengan sigap menopang tubuh Mualimah yang melemah, mendengar kenyataan anak kesayangannya tega berbuat seperti itu. Ini bukan kali pertama.
"Ibu... Ibu... Maafin Hafiz, Bu. Hafiz terpaksa melakukannya," ucap Hafiz yang kini tak berdaya, berlutut di hadapan sang Ibunda.
"Kamus simpan semua alasannya mu itu anak muda. Sekarang Ibumu sedang lemah, segala alasanmu juga tak akan didengar olehnya," geram Tati. Ia semakin marah melihat Hafiz yang terus berupaya membela diri. Benar-benar tidak tahu diri.
Mualimah dibawa menuju kamarnya, ia dibaringkan di sana agar lebih tenang. Hafiz kesana kemari kebingungan memanggil tetangga yang bisa dimintai tolong. Disaat yang sama, Mahmud beserta dua anaknya pulang dari toko, berhubung hari juga sudah senja. Sesampainya di rumah, ia dikejutkan dengan keadaan sang istri yang terbaring lemah, ada apa ini? Pagi tadi saat meminta izin, ia ingat kalau keadaan Mualimah baik-baik saja. Apa telaj terjadi sesuatu? Hatinya bertanya-tanya. Ia duduk di tepi kasur, membelai lembut tangan istri, dengan wajah penuh tanda tanya, Mahmud bertanya "Ibu kenapa? Tadi pagi masih sehat bugar," belaian tangan suami disambut mesra oleh Mualimah, dengan bahasa tubuh melirik ke arah Tati yang berdiri di depan mereka.
"Yah, kenalin, ini Tati, teman SMA Ibu. Beliau ternyata salah satu jemaah pengajian Hafiz dua minggu lalu,"
Mahmud menyambut Tati dengan anggukan dan senyuman, lalu mengalihkan pandangannya kembali pada sang istri, "Lagi temu kangen dengan teman lama, kenapa jadi sakit begini?"
Kembali Mahmud mempertanyakan keadaan istrinya.
"Tati tadi bertemu Hafiz, lalu Tati bertanya pada Ibu, apa benar Ibu adalah orang tua Hafiz, soalnya saat pengajian kemarin, Hafiz mengaku sebagai anak pemilik pesantren, bukan anak pedagang keliling seperti kita."
"Astagfirullah... Ini sudah yang kedua kali ia melakukan ini pada kita, Bu. Mau sampai kapan Ibu menutup mata Ibu atas semua tindakan Hafiz. Mungkin benar, ia malu memiliki orang tua seperti kita, Bu. Hanya penjual alat shalat keliling," tutur Mahmud dengan wajah lesu. Ia sudah tak lagi terkejut, ia sudah menyadari bahwa anak kesayangan mereka malu memiliki orang tua miskin.
"Apa? Ini kedua kalinya? Maaf, bukan saya bermaksud lancang untuk ikut campur keluarga kalian. Tapi, kenapa Hafiz tega seperti ini?" tanya Tati masih tak percaya, mengapa ada anak yang begitu tega berlaku seperti ini, bukan ia tak paham agama, ia justru sangat paham. Namun, apakah dia lupa bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua? Apa dia lupa bahwa azab yang Allah segerakan di dunia adalah azab bagi anak yang durhaka pada orangtuanya? Astagfirullah..
"Dia malu, dia malu dengan teman-temannya yang memiliki orang tua kaya, berada, memiliki jabatan dan posisi penting. Dibanding kami, hanya orangtua biasa, dari kampung dan bergantung pada dagangan mukena serta sajadah," Ucap Mahmud dengan wajah lebih tenang, seperti ikhlas menerima takdir bahwa sang anak telah jelas durhaka padanya.
"Saya sudah ikhlas, jika nasib kami memiliki anak seperti Hafiz. Bagi saya, dia ada atau tidak ada lagi di rumah ini bukan hal yang penting, bahkan ketika di luar sana ia tak pernah menganggap kami orang tuanya juga saya sudah ikhlas, Bu. Saya sudah tahu sejak lama, anak kesayanganmu itu mengaku pada teman-temannya bahwa orang tuanya adalah orang kaya, pemilik pesantren, kita hanya dianggap sebagai paman dan bibi yang telah mengurusnya sejak kecil, jelas saya pernah mendengarnya, Bu. Sudah tidak heran lagi, mengapa ia seperti itu. Bagi saya tidak masalah ia tak menganggap saya sebagai Ayahnya. Tapi jangan sekali-sekali ia tak menganggap Ibu sebagai orang yang melahirkannya, hati saya sakit sekali."
Mualimah dan Tati terdiam, mereka tak menyangka hati Mahmud sudah hambar untuk anaknya, bahkan kata ikhlas yang terucap, sudah seperti ucapan seorang Ayah yang ditinggal mati anaknya. Hafiz sudah tak ada lagi dalam hidupnya. Baginya, anaknya hanya dua saja yaitu Mumtaz dan Yusuf. Maka sejak lama ia sudah memberi wasiat agar Yusuf lah yang kelak diminta untuk menjaga Mualimah dan Mumtaz - Kakanya.
Allahuakbar...allahuakbaru... Asyhaduallaillahaillahu...
"Bu, saya pamit ya, mau ke masjid dulu. Ibu istirahat di sini, nanti Mumtaz akan datang membawa makanan, Ibu harus makan banyak supaya bisa minum obat. Yusuf dan Mumtaz di sini saja ya, Nak. Jaga Ibu kalian baik-baik. Bahagiakan dia. Senangkan hatinya, jangan pernah sakiti hatinya. Bapak pulang ba'da Isya, Bu." ucap Mahmud seraya mengusap-usap kepala kedua anaknya, Mahmud memang selalu berusaha untuk shalat berjamaah di masjid, dia selalu ajarkan itu pada anak laki-lakinya, tak terkecuali Hafiz. Jika biasanya ia turut serta membawa Yusuf, kali ini ia ingin berjamaah di masjid tanpa membawa Yusuf, biar lah Yusuf tetap di sisi Mualimah.
Mahmud berjalan perlahan keluar menuju masjid, tidak ada yang berbeda, hanya raut wajah tenang Ayah tiga anak ini seperti kembali, wajahnya teduh, tenang, dan selalu bijak dalam bersikap, seolah menjadi penenang tersendiri bagi Mumtaz. Artinya sang Ayah telah ikhlas, Ayahnya akan kembali seperti semula, penuh wibawa.
Shalat Isya berjamaah telah usai, Mumtaz yang berada di kamar, setelah menyelesaikan kewajibannya merasa sedikit terganggu dengan suara ramai-ramai dari arah luar. Gegas ia keluar melihat ada apa yang terjadi.
Tampak dua bapak-bapak yang selalu menjadi teman Ayah berjamaah di masjid. Mereka berlari tergopoh, dengan napas terengah-engah, "Assalamu'alaikum Yusuf, Mumtaz, Mualimah," ucapan salam dari pak Karno terdengar.
"Waalaikumussalam, Pak," sahut Yusuf yang keluar dari kamar Ibu. "Pak Mah...Mah...mud. Cepat kalian ke masjid," ujar Pak Karno tersendat. "Ada apa ini, Pak?" tanya Mumtaz. "A...Ayah kalian sudah tidak ada."
Setelah ucapan terakhir Pak Karno, dunia terasa runtuh, gelap. Mumtaz ambruk. Mualimah kembali melemah, masih dibantu Tati temannya, Mualimah dibopong berjalan menuju masjid bersama dengan Yusuf. Mumtaz? Masih belum sadarkan diri.
Sesampainya di masjid, betapa hancur hati mereka yang melihat Mahmud meninggal dalam keadaan bersujud. Ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, keadaan baik yang selalu diinginkan setiap orang. Ia pergi meninggalkan semuanya dalam keadaan penuh keikhlasan, penuh ketaqwaan. Ia serahkan keluarganya pada Allah semata pada bait-bait doa yang ia ucapkan terakhir kali dalam sujud terakhirnya. Sujud terakhir untuk shalat Isya terakhirnya. Juga kata-katanya yang ia sampaikan sebelum pergi ke masjid, adalah kata-kata terakhir untuk keluarganya.
TAMAT






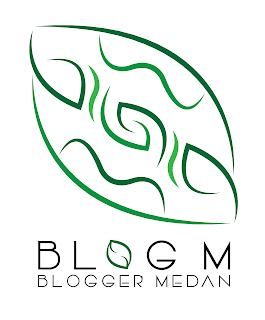
Komentar
Posting Komentar